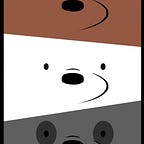tw: chronical illness (minor character), family issues
Lebih dari dua dekade saling kenal, sudah jadi ritual kalau ada yang bete Acan dan Wijay harus makan es krim. Waktu kecil, es krimnya masih es krim paling murah di Indomaret. Jaman kuliah, berubah jadi Aice dan Glico Wings. Sempet juga di Mixue waktu magang, soalnya gaji intern Acan habis di transport dan Wijay pusing membayar sewa studio untuk ngeband. Di umur 24, dengan karir bermusik Wijay yang mulai naik dan Acan yang gajinya nggak UMR lagi, pilihan es krim mereka sedikit lebih beragam.
Kali ini, mereka memilih untuk makan es krim ragusa di mobil. Overpriced nggak? Iya, kalau jajan yang lain. Ayahnya Acan suka becanda kalau otak-otak yang dijual suka fitness soalnya ukurannya makin kecil dari tahun ke tahun. Tapi tetap saja nggak lengkap kalau nggak sekalian jajan otak-otak dan rujak juhi.
“Kamu bete kenapa?” Tanya Wijay. “Bunda hasil medical checkupnya aman?”
Acan lantas mencibir, “Not really? I don’t know.”
“Mau ngomongin?” Tanyanya kembali.
“Kind of,” jawabnya. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan, “Bunda harus ngecek ke dokter obgyn karena ada indikasi lesion atau apa gitu di rahimnya, kayak ada yang nggak beres. Ada sel yang terlalu besar gitu, aku gak terlalu paham juga.”
“Kapan mau ke dokter? Aku bisa anter,” kata Wijay langsung.
“Itu lah. Aku gak paham ini aku denial atau nggak ya, tapi menurutku ini bukan hal yang harus dipusingin banget. Bunda tuh udah gak tenang stress sendiri takut kanker. Tapi kan there is no point in worrying juga lho, nggak produktif.”
“Hmm.”
“Ini bunda udah heboh, ngomong kalau dia kenapa-kenapa yang ngurusin ayah sama nenek siapa, yang ngurus rumah siapa, buat apa coba?” Keluh Acan, “Aku beneran nggak bisa handle kalau bunda udah nggak rasional. Toh dipikirin sampe gimana juga nggak akan ngerubah apa-apa,” lanjut Acan.
“Kalau gitu lebih cepat lebih baik nggak sih, biar bunda nggak kepikiran terus?” Tanya Jay dengan tenang, sudah terbiasa menjawab Acan kalau seperti ini. Ia tahu kekasihnya hanya perlu validasi, bukan Acan namanya kalau nggak cepat mengambil keputusan.
“Kita besok kan mau housewarming apartemen barunya Surya, paginya udah janji mau beli kado bareng Kak Radit juga. Terus bunda tuh aneh, anaknya ada dua tapi maunya cuma ditemenin aku,” Acan melanjutkan. “Kesel.”
“Ya Radit juga bisa beli kado sendiri kali, Can, nggak usah kamu temenin,” kata Wijay.
“Emang, udah aku cancel. Tetep aja aku kesel, aku benci banget kalau harus batalin janji kayak gini.”
“I know.”
“Bete,” Acan kembali cemberut. “Aku paling nggak bisa nih kalau bunda udah anxiety kayak gini, nular beneran deh.”
“Kamu sendiri juga khawatir kan sebenernya?” Tanya Wijay. “Nggak apa-apa, Can, kalau kamu juga khawatir. Wajar kok.”
“Gak logis kalau aku khawatir tentang hal yang belum bisa dikhawatirkan juga,” balas Acan, hampir seperti melafalkan mantra dari psikolognya. “Beneran deh, apa karena aku ISTP ya?”
“Mungkin,” Wijay mengangkat bahunya, tidak hafal MBTI selain ekstrovert dan introvert. Yang terobsesi sama hal-hal berbau pseudoscience kayak MBTI dan bahkan astrologi itu Acan, bukan dia. “Berarti jadinya besok? Aku temenin, ya.”
“Setiap kamu mau nemenin aku gini aku kesel banget karena harusnya kakak aku yang nemenin,” aku Acan. “Tapi temenin.”
“Bang Dion udah tau?”
“Nggak, aku mau gatekeep infonya.”
“Lah, kan dia anaknya bunda juga.”
“Ya biarin aja, toh dia juga nengok bunda di rumah aja nggak mau sejak nikah,” ucap Acan kesal. “Kalau mau tau ya tanya kabar emaknya lah minimal, lah ini kagak. Emang aku anak tunggal gitu? Capek juga kali aku mikirin rumah, aku pengen seneng-seneng juga.”
Kalau Wijay nggak setuju dengan perkataan Acan, nggak diutarakan. “It will be okay, Can. Kamu tau kan tante aku, kakaknya papi? Dia waktu itu kista terus rahimnya diangkat, sehat kok sekarang. Mau coba ngobrol sama dia juga biar lebih tenang?”
Acan menggelengkan kepalanya, “Ke dokter aja dulu.”
“Oke,” Wijay mengangguk. “Makan tuh es krimnya, udah mencair.”
Sebuah tawa kecil langsung keluar dari diri Acan. Ia menyuap sundaenya dengan senyum di bibirnya, memandang Wijay yang masih sibuk menghabiskan rujak juhinya. “Terima kasih ya, this made me feel much better. Kamu terus kayaknya yang jadi terbebani, pas ayah stroke juga.”
“Kita udah kenal berapa lama sih? Kaku amat,” balas Wijay.
“Nggak, maksudnya, mungkin lebih gampang pacaran sama yang keluarganya lebih… beres gitu nggak sih?” Kata Acan. “Aku kalau ngeliat keluarga kamu tuh suka iri sedikit sebenernya.”
“Apaan sih? Ngelantur,” dahi Wijay mengernyit. “Keluarga kamu berusaha keras banget buat kamu, lagian ayah sama bunda juga selalu ikhlas anak perempuannya dari kecil diintilin melulu sama aku.”
“Yang ada kita ngintilin Radit nggak sih?” Canda Acan, berusaha meringankan suasana. Acan yang selalu kesulitan berbicara serius, bersembunyi dibalik humor.
“Tapi yang nampung aku kalau papi sama mami lembur kan kamu,” Wijay mengingatkan. “Aku sayang sama keluarga kamu tuh udah kayak aku sayang sama papi mami, Can, jadi jangan pernah ngomong kayak gitu lagi, aku maunya sama kamu.”
Acan terdiam, wajahnya memerah. Berteman berbelas tahun sebelum mulai berpacaran berarti mereka jarang ngomong kayak gini, selalu santai, banyak yang bilang mereka temenan dan pacaran nggak ada bedanya. Mungkin karena terlanjur nyaman dari awal, bulan pertama pacaran aja Acan masih mau mengubur diri setiap Wijay memanggilnya sayang.
Kadang perempuan itu berpikir, mau mereka pacaran atau nggak pun mereka akan tetap begini. Mungkin tanpa panggilan sayang, yang pasti nggak akan ada ciuman atau afeksi romantis, tapi Ia akan tetap sesayang ini ke Wijay. Perasaan mereka memang mungkin lebih dari sekedar perasaan romantis, rasanya jauh lebih dalam dari itu.
“Aku juga. Cuma kayak, apa ya, ini kayaknya karena kesel sama abang aku juga,” Acan berusaha menjelaskan kepada kekasihnya itu. “Kok bisa kamu lebih peduli sama aku, sama keluarga aku, daripada abang aku yang udah jelas satu darah sama ayah bunda?”
Abangnya Acan, Dion, terpaut empat tahun dari Acan. Kalau Acan harus menjelaskan di titik mana mereka jadi tidak dekat, Ia juga tidak dapat menjawab. Mungkin saat Dion menyalahkan orang tuanya karena tidak sekaya orang tua anak-anak lain yang dapat memberikan anak mereka fasilitas lebih, mungkin ketika Dion memutuskan Ia tidak mau terlibat dengan urusan rumah sama sekali setelah menikah. Acan menebak itu alasan mengapa hobinya ngintilin Radit dari kecil, semacam kakak pengganti karena yang sedarah dengannya nggak peduli.
“I know,” angguk Wijay, lebih netral. “Tapi aku juga nggak keberatan, Can, untuk ngurusin keluarga kamu. Jadi jangan terlalu dipikirin Bang Dionnya.”
“Sayang…”
“Aku tau sekarang emang aku masih bergantung sama papi juga meskipun band aku mulai naik, tapi I’m working on something dan semoga nanti aku cukup stabil untuk ngurusin kamu, ngurusin ayah bunda, ngurusin papi mami aku juga.” Cara Wijay mengucapkan kata-katanya seakan itu hal yang diucapkan di altar pernikahan, bukan di pinggir jalan dengan rujak juhi di pangkuannya.
Acan pengen nangis rasanya, “Kita usahain bareng-bareng.”
“Duh aku mau nyium kamu tapi bau juhi,” keluh Wijay, memecahkan suasana serius di antara mereka berdua. “Peluk aja sini,” Ia menarik Acan untuk memeluknya, terhalang konsol mobil di antara mereka.
Acan tertawa lepas, “Aku sayang banget sama kamu.”
“Aku juga sayang banget sama kamu, Can.”
“Tapi kamu kalau mau ngelamar aku nanti jangan di mobil ya,” lanjut perempuan itu. “Nanti, bukan sekarang, kalau kamu ngelamar sekarang aku tolak soalnya.”
“Iya, tuan putri, iya,” Wijay tidak bisa menahan diri untuk mencium pipi Acan.
“Ih, bau juhi!”