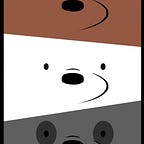Kalau Arin nggak lagi berantakan, mungkin Arin akan berkomentar ketika Hisyam memasang album Nothing Personalnya All Time Low. Tapi Arin cuma bisa diam, memandang ke luar jendela mobil Hisyam di macetnya lalu lintas Jakarta. Kalau ada yang bilang Ia akan ada di mobil Hisyam malam ini, Arin pasti akan memanggil orang itu gila, tapi kenyataannya Ia benar-benar di sini.
Dasar badut.
“Alamatnya masih sama?”
“Masih.”
“Sering kayak gini?” Tanya Hisyam lagi.
“Biasanya cuma diancem lewat telpon, kita nggak pernah angkat,” jawab Arin.
“Bilang bunda lo udah di jalan pulang,” kata Hisyam. “Bang Arvian sekarang nggak tinggal sama kalian kan?”
“Bang Arvian pindah ke BSD.”
“Oke.”
Lalu mobil itu sunyi selain suara nyanyian Alex Gaskarth yang bernyanyi tentang kisah cinta remaja dan teenage angst. Sebenarnya, kalau Arin pikir, Hisyam selalu punya soft spot untuk bunda. Bunda bertutur santai di hadapan maminya Hisyam yang berwatak keras, nggak pernah memaksa Arin harus jadi macam-macam ketika Hisyam selalu dituntut mendapatkan nilai sempurna.
Macetnya Jakarta lebih pemaaf malam ini dan mereka bisa melihat gerombolan debt collector itu begitu belok ke jalan rumah Arin. Hisyam menghentikan mobilnya pas di depan pagar rumah Arin dan melepaskan sabuk pengamannya. Wajah preman itu bringas, Arin paham kenapa tetangga mereka, Wadi, dan Pak RT sama-sama nggak berani.
“Nyari siapa pak?” Tanya Hisyam begitu keluar dari sisi pengemudi, tidak ada takutnya sama sekali dengan belati yang ada di tangan preman itu.
“Arvian.”
“Orangnya nggak tinggal di sini pak, rumahnya di BSD bukan di sini,” Hisyam masih menjawab dengan tenang. “Mending bapak pulang aja, nggak ada yang bisa bantu bapak juga di sini.”
“Jangan nyuruh pulang-pulang aja pak, saya kan di sini menjalankan tugas. Saya harus ketemu dengan keluarganya Bapak Arvian, sudah berbulan-bulan hilang dan nggak bayar hutang. Sekarang bapak siapa? Keluarganya?”
“Iya, saya bayar.”
“Jangan iya-iya aja — “
“Pak,” Hisyam memotong perkataan bapak itu. “Coba saya bicara sama bos bapak, yang nyuruh bapak ke sini. Bapak di bawah siapa? Pak Ian? Pak Edo?”
Preman itu terlihat terkejut Hisyam mengetahui nama-nama tersebut. “Edo, pak.”
“Coba bapak telpon sekarang, bilang Hisyam Suwardana mau ngomong.”
“Emang bapak siapa nyuruh-nyuruh saya?”
“Telpon aja pak, nanti bapak juga tahu.”
Arin cuma bisa bengong melihat gerombolan preman itu mohon-mohon maaf ke Hisyam sebelum pulang, tidak ketinggalan menunduk di hadapan Arin yang hanya bisa nonton dari tadi. Bunda, yang nonton dari balik jendela, langsung keluar dan membuka pagar ketika mereka pergi.
“Bun,” Arin langsung memeluk perempuan itu. “Maaf ya, tadi agak lama, macet banget.”
Atensi bunda bukan ke Arin, tapi ke Hisyam yang masih berdiri dengan canggung. “Kamu nggak berubah sama sekali ya dari dulu,” komentarnya ketika melihat Hisyam. “Gimana mami sama papi?”
“Sehat, bun,” jawab Hisyam.
“Kalian memang masih berhubungan ya?” Tanya bunda, tahu betul tentang segala curhatan Arin tentang jahatnya Hisyam, tentang permintaan Arin pindah sekolah. “Bunda kira udah lost contact waktu Arin pindah sekolah.”
“Kebetulan perusahaannya Arin jadi konsultan kita,” Hisyam berbohong.
Bunda mengernyit, “Emang apa hubungannya riset ekonomi sama perusahaan kamu, Syam?”
“Biasa, bun, regulasi lingkungannya perusahaan, kan aku juga ngurus ekonomi hijau gitu,” Arin menjawab. “Masuk duluan aja bun, aku ada yang harus diomongin lagi sama Hisyam soal kerjaan.”
“Nggak mau ngobrol di dalem?” Tanya bunda, walaupun Arin tahu itu basa basi. Bunda yang mengutuk keluarga Hisyam sampai nangis berkepanjangan, yang mungkin selalu menyebut nama Hisyam dengan konotasi negatif dalam sholatnya, nggak mungkin menawarkan hal itu. Tapi bunda juga lebih bisa mengontrol emosinya daripada Arin.
“Nggak usah, bun, nanti malah ngerepotin,” jawab Hisyam dengan senyum pertamanya yang Arin lihat hari ini.
“Thanks,” kata Arin begitu bunda masuk rumah. Mereka ngobrol di teras rumah Arin, sama-sama memilih untuk tetap berdiri. Sama-sama tidak mau berlama-lama.
“You owe me now,” kata Hisyam, seperti telah memenangkan sesuatu. “So I need you to show up on the 14th and cooperate with me, whatever the will says.”
Arin menghela napas panjang. “Fine. Tadi lo ngomong apa sama premannya? Lo kenal sama mereka?”
Tawa yang keluar dari Hisyam sangat mengejek. “Kadang ada orang-orang yang nggak takut dengan nama keluarga gue, jadi harus ada… tekanan dikit, kali ya. Anyway, mereka di bawah bokap. Besok utang abang lo gue bayar.”
“Bayarannya?”
“Your cooperation, gampang kan?”